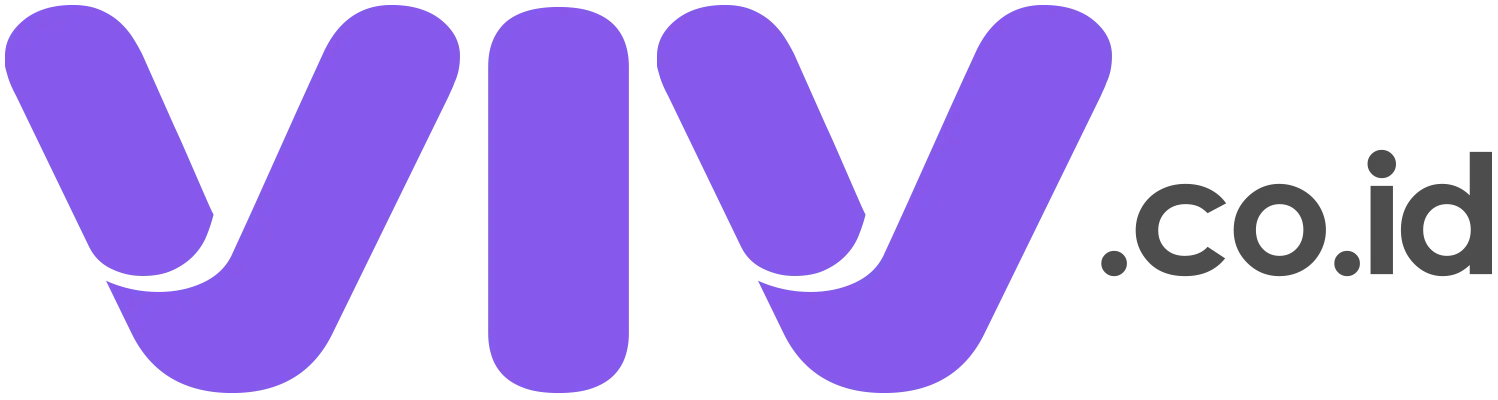Benarkah Perkebunan Kelapa Sawit Picu Bencana di Sumatera? Ini Fakta Lingkungan yang Perlu Anda Tahu

tanda tanya-geralt/pixabay-
Benarkah Perkebunan Kelapa Sawit Picu Bencana di Sumatera? Ini Fakta Lingkungan yang Perlu Anda Tahu
Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dalam beberapa pekan terakhir kembali memicu perdebatan publik. Di tengah duka dan upaya pemulihan, muncul narasi luas di media sosial dan pemberitaan lokal yang mengaitkan bencana itu dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pertanyaannya: benarkah kelapa sawit menjadi dalang bencana alam tersebut? Ataukah ada faktor lain yang tak kalah penting yang luput dari sorotan?
Sumatera, Lumbung Sawit Nasional yang Rentan Bencana
Sumatera memang dikenal sebagai salah satu jantung produksi kelapa sawit Indonesia. Provinsi Riau, misalnya, menjadi penyumbang utama minyak sawit nasional dengan total luas kebun mencapai lebih dari 3 juta hektar. Wilayah seperti Kampar, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, dan Indragiri Hilir menjadi sentra produksi andalan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.
Namun, Riau bukan satu-satunya. Perkebunan sawit juga tersebar luas di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Barat. Kehadiran perkebunan ini membawa dampak ekonomi yang masif, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pendapatan daerah. Namun, di balik kejayaan emas hijau itu, muncul kekhawatiran serius tentang keberlanjutan lingkungan.
Sawit dan Kerentanan Ekologis: Akar Tunggal yang Tak Mampu Menahan Tanah
Salah satu argumen paling kritis terhadap perkebunan kelapa sawit adalah sistem perakarannya yang dangkal dan bersifat tunggal. Berbeda dengan hutan alam yang memiliki tajuk dan akar dalam yang kompleks, akar sawit tidak mampu menahan tanah secara optimal. Ketika hujan deras mengguyur, terutama di daerah perbukitan atau lereng curam, tanah menjadi rentan tergerus.
“Perkebunan sawit memang efisien dalam produksi, tapi dari sisi ekologi, ia jauh lebih rentan terhadap erosi dan limpasan permukaan dibanding hutan asli,” ungkap seorang peneliti lingkungan dari Universitas Andalas, dalam wawancara terpisah.
Hal ini diperparah oleh praktik pembukaan lahan yang kerap dilakukan secara masif dan tidak memperhatikan tata ruang yang berkelanjutan. Hutan primer yang seharusnya menjadi penyangga ekologis justru dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Akibatnya, saat musim hujan tiba, tidak ada lagi sistem alami yang menyerap dan mengatur aliran air, sehingga risiko banjir dan longsor meningkat drastis.
Deforestasi, Emisi Karbon, dan Kepunahan Spesies
Bukan hanya soal banjir dan tanah longsor, perluasan perkebunan kelapa sawit juga dikaitkan dengan laju deforestasi tercepat di Asia Tenggara. Menurut laporan yang dirilis oleh Mertani pada Kamis, 4 Desember 2025, konversi hutan menjadi perkebunan sawit merupakan faktor utama hilangnya tutupan hutan alam di kawasan ini.
Proses pembukaan lahan—baik melalui penebangan langsung maupun pembakaran—tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Indonesia, sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar akibat perubahan penggunaan lahan, kerap menjadi sorotan internasional terkait hal ini.
Selain itu, habitat satwa endemik seperti harimau Sumatera, orangutan, tapir, dan berbagai jenis burung langka semakin terancam. Banyak dari spesies ini bergantung pada hutan primer yang kini perlahan lenyap digantikan oleh barisan pohon sawit yang seragam dan tak ramah keanekaragaman hayati.
Menimbang Manfaat Ekonomi vs. Biaya Ekologis
Tentu saja, menyalahkan kelapa sawit secara sepihak bukanlah solusi. Faktanya, industri ini menyumbang lebih dari 11% ekspor non-migas Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Bagi banyak keluarga, sawit adalah sumber penghidupan utama.
Namun, tantangannya justru terletak pada bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Praktik perkebunan berkelanjutan—seperti yang diusung oleh sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)—bisa menjadi jalan tengah, asalkan benar-benar diterapkan tanpa kompromi.