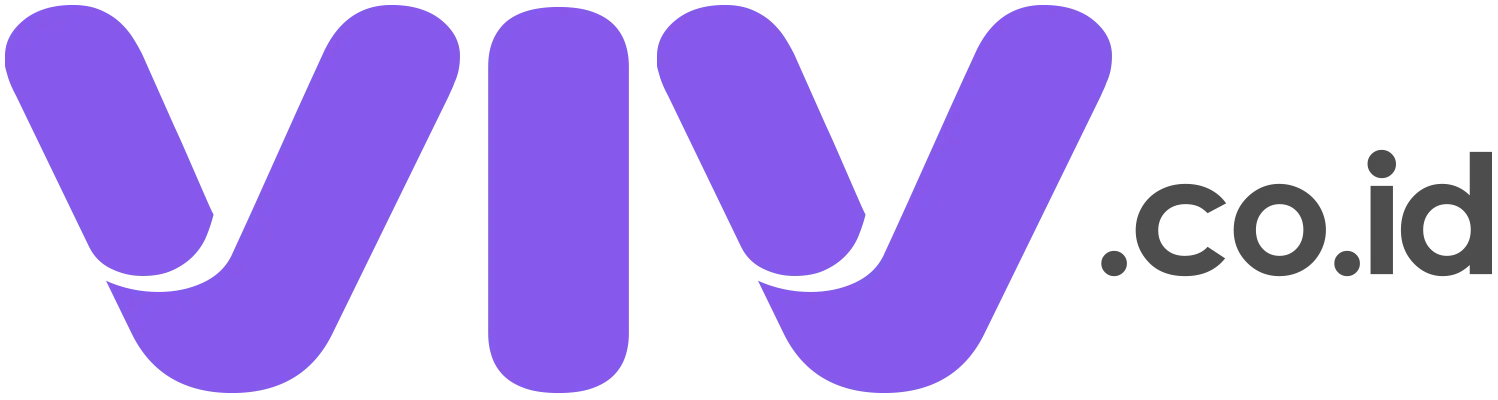Teks Khutbah Jumat 9 Januari 2026: Kekayaan Sejati Bukan di Rekening, Tapi di Hati – Refleksi Spiritual di Tengah Gempuran Materialisme

masjid-xegxef/pixabay-
Teks Khutbah Jumat 9 Januari 2026: Kekayaan Sejati Bukan di Rekening, Tapi di Hati – Refleksi Spiritual di Tengah Gempuran Materialisme
Di tengah hiruk-pikuk dunia yang kian mengagungkan pencapaian materi, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang layak direnungkan: Apa sebenarnya arti kekayaan? Bagi sebagian besar orang, kekayaan kerap diukur dari jumlah saldo di rekening, koleksi mobil mewah, atau luasnya rumah di kawasan elite. Namun, dalam khutbah Jumat tanggal 9 Januari 2026, umat Muslim diingatkan kembali pada satu kebenaran abadi: kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan kekayaan hati.
Dalam naskah khutbah berjudul “Kekayaan Sejati Adalah Kaya Hati”, khatib mengajak jamaah untuk meninjau ulang persepsi kita tentang kesuksesan, kepuasan hidup, dan makna kesejatian dalam beragama. Artikel ini menyajikan ulang inti khutbah tersebut dengan pendekatan jurnalistik modern, dikembangkan menjadi narasi yang lebih mengalir, reflektif, dan relevan dengan tantangan kehidupan kontemporer—tanpa mengurangi esensi ajaran Islam yang universal.
Kekeliruan Modern: Mengukur Kekayaan hanya dengan Meteran Dunia
Dalam masyarakat konsumtif hari ini, nilai seseorang kerap dinilai berdasarkan penampilan luar: pakaian branded, gadget terbaru, hingga liburan mewah yang diunggah di media sosial. Tren ini secara tidak sadar menciptakan tekanan sosial yang membuat banyak orang merasa “belum cukup” meski sebenarnya telah diberkahi nikmat yang melimpah.
Namun, Islam datang bukan untuk mengikuti arus dunia, melainkan untuk meluruskan arah hidup. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:
“Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati (ghina an-nafs).”
(Muttafaqun ‘Alaih)
Kalimat singkat ini mengandung revolusi mental yang luar biasa. Di sini, Islam tidak menolak harta—malah mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berdagang. Tapi Islam menegaskan bahwa harta hanya alat, bukan tujuan. Dan kepuasan batin—yang lahir dari rasa syukur, ketenangan, dan ketergantungan hanya kepada Allah—adalah harta yang tak ternilai harganya.
Kisah Qarun: Simbol Kekayaan Tanpa Jiwa
Salah satu ilustrasi paling menohok dalam Al-Qur’an tentang bahaya kekayaan tanpa keimanan adalah kisah Qarun. Ia adalah sosok yang memiliki kekayaan luar biasa hingga “kuncinya saja dibutuhkan kelompok kuat untuk mengangkatnya.” Namun, kekayaannya tidak menumbuhkan kerendahan hati—justru memupuk kesombongan.
Allah menceritakan dalam Surah Al-Qashash ayat 76–82 bagaimana Qarun akhirnya ditelan bumi bersama seluruh hartanya karena kesombongannya. Ini adalah peringatan abadi: harta tanpa ketakwaan adalah bom waktu yang siap meledakkan jiwa dari dalam.
Sayangnya, banyak di antara kita hari ini hidup seperti Qarun modern—punya segalanya, tapi jiwanya hampa. Mereka tidur di kasur empuk, tapi pikirannya dipenuhi kecemasan. Mereka makan dari piring emas, tapi hatinya tak pernah kenyang. Inilah yang disebut oleh Nabi sebagai “manhum”—orang yang rakus terhadap dunia.
“Dua golongan orang yang rakus yang tidak pernah merasa kenyang: orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah kenyang darinya; dan orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah kenyang darinya.”
(HR. Al-Hakim)
Ironisnya, orang yang rakus ilmu disebutkan bersama orang rakus dunia—bukan untuk menyamakan, tapi untuk menunjukkan betapa ganasnya sifat ‘rakus’ itu sendiri. Namun, satu berujung pada cahaya, yang lain pada kegelapan.
Teladan Para Nabi: Kekayaan dalam Ketergantungan kepada Allah
Jika Qarun menjadi contoh negatif, maka para Nabi adalah cerminan sempurna dari orang kaya jiwa.
Saat Ratu Saba’ mengirim hadiah mewah kepada Nabi Sulaiman ‘alaihissalam, beliau menjawab dengan tenang:
“Apa yang Allah berikan kepadaku (kenabian dan hidayah) lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu.”
(QS. An-Naml: 36)
Demikian pula Zulkarnain, ketika ditawari upah besar untuk membangun bendungan, ia berkata:
“Apa yang telah Tuhanku anugerahkan kepadaku adalah lebih baik.”
(QS. Al-Kahfi: 95)
Mereka tidak menolak dunia, tapi tidak menjadikannya pusat cinta. Mereka kaya karena merasa cukup dengan Allah, bukan karena memiliki emas. Dalam bahasa tasawuf, ini disebut “al-ghina ‘an al-khalq”—merasa cukup tanpa bergantung pada makhluk.
Terapi Spiritual di Era Digital: Berhenti Membandingkan, Mulai Bersyukur
Salah satu akar penderitaan jiwa di era media sosial adalah kebiasaan membandingkan diri. Kita melihat foto liburan teman di Maladewa, lalu merasa hidup kita “gagal.” Kita lihat influencer makan di restoran bintang lima, lalu merasa nasi sederhana di rumah “kurang berkelas.”
Padahal, Rasulullah ﷺ mengajarkan terapi sederhana namun ampuh:
“Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam urusan dunia), dan jangan pandang orang yang berada di atasmu, agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah.”
(HR. Muslim)
Terapi ini bukan berarti menutup mata terhadap ketidakadilan, melainkan melatih perspektif syukur.
Saat Anda sehat, ingatlah jutaan orang yang terbaring sakit.
Saat Anda aman tidur malam, ingatlah saudara-saudara di Gaza, Sudan, atau Suriah yang hidup dalam ketakutan.
Saat Anda makan nasi hangat, ingatlah anak-anak yang rela berjalan puluhan kilometer hanya untuk sepotong roti.
Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
“Barangsiapa yang di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dan seluruh isinya telah dikumpulkan untuknya.”
Bukankah ini definisi kekayaan yang paling adil dan universal?
Langkah Nyata Menuju Kekayaan Hati
Lantas, bagaimana cara meraih kekayaan jiwa di tengah arus materialisme yang begitu deras? Khutbah Jumat ini menawarkan tiga langkah praktis:
Berdoa Meminta “Al-Ghina”
Bacalah doa yang diajarkan Nabi:
“Allahumma innâ nas’alukal-hudâ wat-tuqâ wal-‘afâfa wal-ghinâ.”
(Ya Allah, kami memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kekayaan jiwa.)
Menjaga ‘Iffah – harga diri spiritual
Jangan biarkan diri tergantung pada pujian, harta, atau status sosial. Cukuplah Allah sebagai sandaran.
Latih Mata untuk Melihat ke Bawah
Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan harian. Buat jurnal nikmat. Setiap malam, tulis tiga hal yang Anda syukuri hari ini—sekecil apa pun.
Penutup: Dunia Ini Fana, Tapi Jiwa Abadi
Di penghujung khutbah, khatib mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tapi siapa diri kita di hadapan Allah. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk “lebih banyak,” Islam mengajak kita untuk “lebih cukup.”