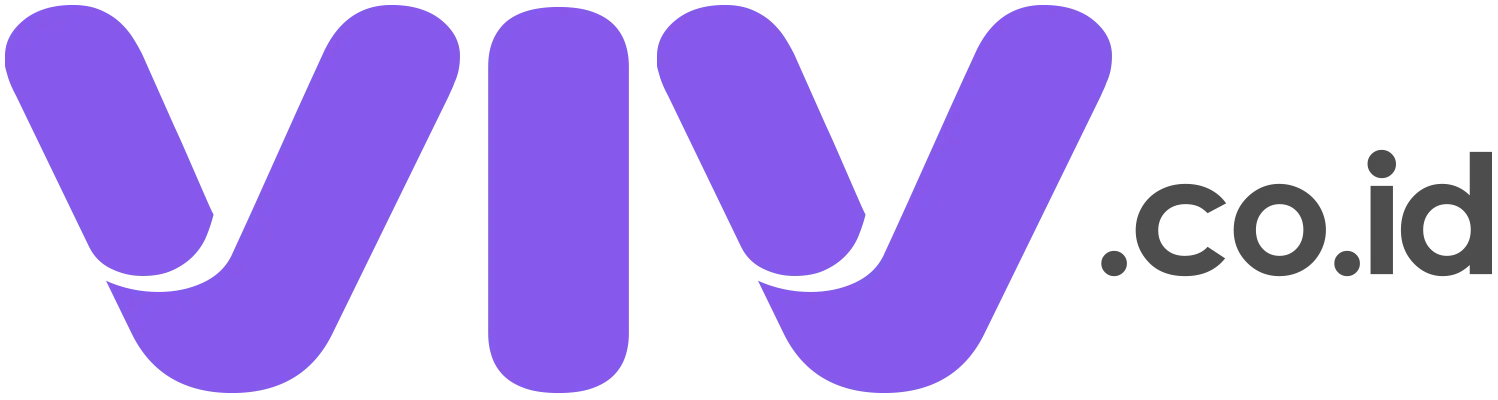Penjarahan Massal di Sibolga: Bukan Sekadar Kriminalitas, Tapi Jeritan Kemanusiaan yang Terabaikan

Penjarahan-Instagram-
Penjarahan Massal di Sibolga: Bukan Sekadar Kriminalitas, Tapi Jeritan Kemanusiaan yang Terabaikan
Di tengah reruntuhan akibat bencana alam yang melanda wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, muncul aksi yang mengejutkan publik: penjarahan massal oleh warga setempat. Namun, di balik citra negatif yang kerap dikaitkan dengan tindakan tersebut, tersembunyi narasi yang jauh lebih kompleks—sebuah campuran antara kelaparan, ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kegagalan respons kemanusiaan.
Alih-alih menghakimi, sejumlah pakar sosial justru mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Sibolga bukan semata-mata masalah hukum atau moral, melainkan cerminan dari krisis multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial-politik. Aksi kolektif itu, menurut para pengamat, lahir dari akumulasi tekanan yang tak tertahankan akibat bantuan kemanusiaan yang tak kunjung datang.
Ketika Harapan Berubah Jadi Frustrasi
Pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Agus Suriadi, menegaskan bahwa penjarahan massal bukanlah tindakan spontan tanpa akar sosial. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi darurat, ketika akses logistik terputus dan komunikasi distribusi bantuan tidak transparan, warga—terutama mereka yang sudah berada di garis kemiskinan jauh sebelum bencana—merasa terdesak untuk bertindak demi kelangsungan hidup.
“Warga berharap bantuan cepat. Ketika harapan itu gagal dipenuhi, muncul frustrasi yang bisa mendorong tindakan ekstrem,” ujar Agus saat dihubungi, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, banyak keluarga di wilayah terdampak sudah hidup dalam kondisi ekonomi yang rapuh bahkan sebelum gempa atau banjir bandang melanda. Mereka bergantung pada penghasilan harian yang kini lenyap karena infrastruktur hancur dan aktivitas ekonomi lumpuh total. Dalam konteks seperti itu, makanan, air bersih, dan obat-obatan menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda—bahkan jika harus mengambil risiko hukum.
Solidaritas yang Berubah Jadi Amarah
Ironisnya, dalam kondisi krisis, solidaritas sosial biasanya justru menguat. Tetangga saling membantu, komunitas gotong royong, dan semangat kebersamaan muncul sebagai benteng pertahanan terhadap kekacauan. Namun, Agus menyoroti bahwa solidaritas tersebut bisa berubah arah—menjadi bentuk protes kolektif—jika pemerintah dianggap absen atau lambat merespons.
“Warga merasa harus bertindak sendiri demi memenuhi kebutuhan kelompoknya,” katanya. “Ketika negara tidak hadir dalam momen kritis, masyarakat mengambil alih, meski caranya tidak sesuai hukum.”
Dalam kasus Sibolga, aksi penjarahan bukanlah perilaku individu yang ingin mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, banyak laporan menyebut barang-barang yang diambil justru dibagikan secara merata di antara warga yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik, bukan sekadar tindak kriminal biasa.
Krisis Kepercayaan: Akar Masalah yang Tak Boleh Diabaikan
Salah satu poin terpenting yang diangkat Agus adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan bencana. Keterlambatan distribusi bantuan tidak hanya berdampak fisik, tapi juga memperlebar jarak psikologis antara rakyat dan negara.
“Penjarahan di Sibolga bukan hanya soal mencari barang. Ini adalah bentuk protes sosial—ekspresi keputusasaan terhadap sistem yang dianggap gagal melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Ketika janji bantuan terus bergema di media namun tak kunjung sampai ke tangan warga, maka kepercayaan itu runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, kepatuhan terhadap hukum pun mulai goyah. Dalam situasi ekstrem, kelangsungan hidup mengalahkan norma sosial—bukan karena warga tidak beretika, tetapi karena mereka merasa ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Momentum untuk Perubahan Sistem Penanggulangan Bencana
Agus Suriadi menekankan bahwa peristiwa di Sibolga harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat maupun daerah. “Ini bukan hanya soal logistik. Pemulihan pasca-bencana harus mencakup pemulihan kepercayaan,” katanya.