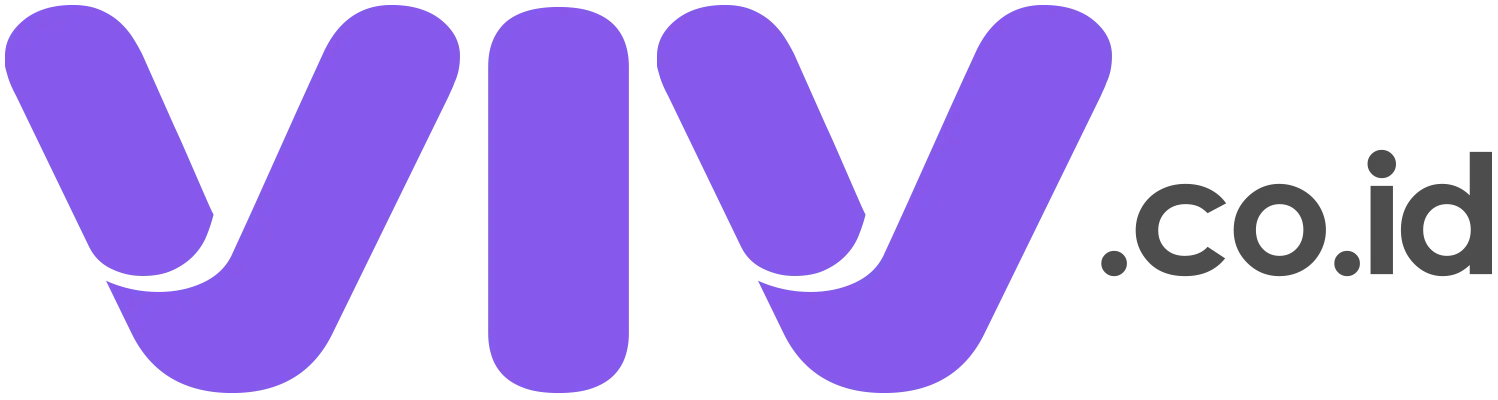Tomiichi Murayama Sakit Apa? Benarkah Akibat Serangan Jantung? Inilah Kronologi Tewasnya Mantan Perdana Menteri Jepang di Usia 101 Tahun

Tomii-Instagram-
Tomiichi Murayama Sakit Apa? Benarkah Akibat Serangan Jantung? Inilah Kronologi Tewasnya Mantan Perdana Menteri Jepang di Usia 101 Tahun
Mantan Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama Tutup Usia di Usia 101 Tahun: Warisan Permintaan Maaf yang Mengguncang Asia
Dunia politik Jepang dan Asia kehilangan salah satu tokoh paling berani dan visioner dalam sejarah modern. Mantan Perdana Menteri Jepang, Tomiichi Murayama, meninggal dunia pada usia 101 tahun di wilayah barat daya Jepang pada Jumat, 17 Oktober 2025. Kabar duka ini langsung memicu gelombang penghormatan dari dalam dan luar negeri, mengingat peran pentingnya dalam memperbaiki hubungan Jepang dengan negara-negara tetangga pasca-Perang Dunia II.
Murayama, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari Juni 1994 hingga Januari 1996, dikenang bukan hanya sebagai pemimpin dari Partai Sosial Demokrat (SDPJ), tetapi juga sebagai sosok yang berani mengakui kesalahan masa lalu bangsanya. Di tengah budaya politik Jepang yang cenderung menghindari pengakuan terbuka atas kekejaman masa perang, Murayama justru tampil beda—dengan keberanian moral yang langka.
Pernyataan Murayama: Permintaan Maaf yang Mengubah Sejarah
Salah satu warisan paling monumental dari kepemimpinan Murayama adalah “Pernyataan Murayama” yang diucapkan pada 15 Agustus 1995, bertepatan dengan peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Dalam pidato bersejarah tersebut, ia menyampaikan “penyesalan yang mendalam” serta “permintaan maaf yang tulus” atas penderitaan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan agresi militer Jepang di Asia.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika diplomatik. Ia menjadi dasar moral bagi kebijakan luar negeri Jepang selama puluhan tahun berikutnya, dan kerap dikutip oleh pemerintah-pemerintah Jepang selanjutnya sebagai komitmen resmi negara terhadap rekonsiliasi sejarah. Bahkan hingga hari ini, “Pernyataan Murayama” dianggap sebagai salah satu dokumen paling penting dalam upaya Jepang membangun kembali kepercayaan dengan Korea Selatan, Tiongkok, Filipina, dan negara-negara Asia lain yang pernah menjadi korban kekejaman imperialisme Jepang.
Langkah Nyata di Balik Kata-Kata
Murayama tidak hanya berhenti pada kata-kata. Ia menerjemahkan penyesalannya menjadi kebijakan konkret. Salah satunya adalah pendirian Asian Women’s Fund pada tahun 1995—sebuah inisiatif semi-pemerintah yang memberikan kompensasi finansial dan surat permintaan maaf langsung dari Perdana Menteri kepada para “wanita penghibur” (comfort women), yaitu perempuan-perempuan yang dipaksa menjadi budak seks oleh militer Kekaisaran Jepang selama perang.
Meski kontroversial karena tidak sepenuhnya menggunakan dana negara, langkah ini tetap dianggap sebagai terobosan besar dalam konteks politik Jepang saat itu, di mana isu tersebut selama puluhan tahun dianggap tabu.
Selain itu, Murayama juga memperjuangkan undang-undang yang memberikan kompensasi lebih adil kepada para penyintas bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ia memahami bahwa rekonsiliasi eksternal harus diimbangi dengan keadilan internal—mengakui penderitaan rakyat Jepang sendiri akibat perang, sekaligus mengakui penderitaan yang mereka timbulkan pada orang lain.
Reformasi dalam Bayangan Krisis
Masa jabatan Murayama berlangsung di tengah badai krisis nasional. Tahun 1995 menjadi salah satu tahun paling kelam dalam sejarah Jepang pasca-perang. Pada Januari, gempa bumi dahsyat Hanshin mengguncang Kobe, menewaskan lebih dari 6.000 orang dan menghancurkan infrastruktur kota. Respons pemerintah yang lambat menuai kritik luas, namun Murayama kemudian memperkuat sistem manajemen bencana nasional sebagai pelajaran berharga.
Tak lama setelah itu, pada Maret 1995, sekte AUM Shinrikyo melancarkan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo, menewaskan belasan orang dan melukai ribuan lainnya. Insiden ini mengguncang rasa aman masyarakat Jepang dan memaksa pemerintah meninjau ulang kebijakan keamanan domestik.
Belum usai dari dua krisis tersebut, pada September 1995, tiga tentara Amerika Serikat di Okinawa dituduh memperkosa seorang gadis sekolah berusia 12 tahun. Insiden ini memicu protes massal di seluruh Jepang, terutama di Okinawa, yang selama puluhan tahun menanggung beban kehadiran pangkalan militer AS. Murayama, meski terikat aliansi dengan Washington, mendesak perundingan ulang status kehadiran pasukan AS di Jepang—langkah yang menunjukkan keberpihakannya pada rakyat biasa.
Kompromi Politik yang Visioner
Sebagai pemimpin dari partai sayap kiri yang secara ideologis menentang keberadaan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), aliansi keamanan dengan AS, serta simbol-simbol nasional seperti bendera Hinomaru dan lagu kebangsaan Kimigayo, Murayama justru menunjukkan fleksibilitas politik yang luar biasa.
Ia mengakui legitimasi JSDF dan perjanjian keamanan Jepang-AS sebagai realitas geopolitik pasca-perang. Keputusan ini memicu perpecahan dalam partainya sendiri, tetapi Murayama bersikeras bahwa stabilitas nasional dan perdamaian regional harus diutamakan di atas dogma ideologis.
Langkah ini membuktikan bahwa Murayama bukan hanya idealis, tapi juga pragmatis—seorang negarawan yang memahami seni berkompromi demi kepentingan bangsa yang lebih besar.