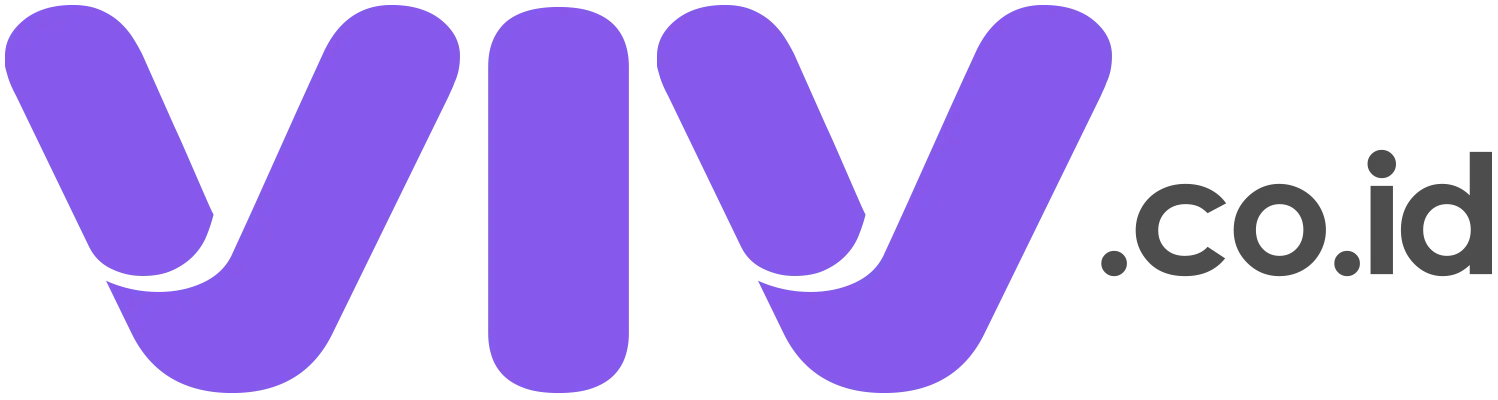Santri di Aceh Bakar Asrama Pesantren Usai Bertahun-tahun Jadi Korban Bullying

Aceh-Instagram-
Santri di Aceh Bakar Asrama Pesantren Usai Bertahun-tahun Jadi Korban Bullying: Tragedi yang Menggugah Kesadaran akan Kesehatan Mental di Lingkungan Pendidikan Agama
Aceh Besar, 6 November 2025 — Sebuah kejadian mencekam terjadi di Pondok Pesantren Babul Maghfirah, Desa Lam Alue Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, pada Kamis dini hari. Seorang santri berusia di bawah umur, diduga kelas 12, sengaja membakar asrama putra tempat ia tinggal. Aksi nekat ini bukan sekadar ledakan amarah sesaat, melainkan puncak dari penderitaan panjang akibat perundungan (bullying) yang bertahun-tahun ia alami tanpa ada yang mendengar.
Kepolisian Resort Banda Aceh, melalui Kombes Pol Joko Heri Purwono, mengonfirmasi bahwa kebakaran yang melanda dua bangunan utama—asrama putra lantai dua dan kantin—terjadi akibat tindakan sengaja. Kamera pengawas (CCTV) merekam dengan jelas adegan mengerikan: seorang remaja berbaju koko, dengan wajah penuh keputusasaan, memegang bahan mudah terbakar—kabel listrik dan triplek—sebelum membakarnya di sudut asrama. Api dengan cepat menjalar ke dinding kayu dan atap, memicu kebakaran besar yang menghanguskan sebagian struktur bangunan.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bangunan asrama yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembelajaran spiritual, berubah menjadi puing-puing hitam yang masih mengeluarkan asap tebal hingga siang hari.
“Sering Disebut Idiot dan Tolol” — Penderitaan yang Tidak Pernah Diungkap
Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku secara terbuka bahwa ia telah menjadi korban perundungan sistematis selama bertahun-tahun oleh teman-teman seangkatannya. Ia mengungkapkan bahwa sehari-hari ia dipanggil “idiot”, “tolol”, “bodoh”, bahkan “sampah” di depan banyak orang. Tidak hanya di kamar asrama, tapi juga di ruang belajar, masjid, hingga saat makan bersama.
“Dia bilang, dia sudah tidak tahan lagi. Dia merasa tidak punya tempat untuk berbicara. Tidak ada yang peduli,” kata Kombes Pol Joko Heri Purwono dalam konferensi pers, Kamis (6/11/2025).
Yang paling menyentuh hati adalah pengakuan pelaku bahwa ia tidak pernah melapor kepada pengasuh, ustadz, atau petugas pesantren. Ia takut dianggap lemah, dihukum lebih berat, atau malah dianggap “mengada-ada”. “Dia bilang, kalau dia lapor, malah akan jadi bahan ejekan baru. Jadi, dia memilih diam. Sampai akhirnya, diam itu meledak,” tambah Kombes Joko.
Sistem yang Gagal Mendengar: Ketika Bullying Dianggap “Hanya Main-main”
Kasus ini bukan sekadar kebakaran. Ini adalah sebuah krisis sistemik dalam lingkungan pendidikan agama yang sering kali mengabaikan aspek psikologis santri. Di banyak pesantren, terutama yang menerapkan disiplin ketat, ekspresi emosi dianggap sebagai tanda kelemahan. Laporan tentang perundungan sering dianggap “masalah kecil”, “gurauan khas remaja”, atau “bagian dari proses pembentukan karakter”.
Padahal, psikolog pendidikan Dr. Aisyah Rahman dari Universitas Syiah Kuala menyatakan, “Bullying di lingkungan religius bukanlah hal yang bisa diabaikan. Justru di tempat yang seharusnya menjadi pelindung spiritual, korban merasa lebih terisolasi. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak mendengar, manusia tidak peduli, dan dirinya sendiri tidak layak diselamatkan.”
Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus bullying di pesantren tidak dilaporkan karena rasa malu, takut dihukum, atau ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan. Kasus Aceh ini adalah contoh nyata bagaimana diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi ledakan bencana.
Pelaku Melarikan Diri, Tapi Tidak Kabur dari Tanggung Jawab
Setelah membakar asrama, pelaku langsung melarikan diri ke rumah orang tuanya di wilayah sekitar. Ia tidak berusaha menyembunyikan diri secara ekstrem. Ia justru menunggu di rumah, seolah menunggu keadilan datang—meski dalam bentuk yang pahit.
Polisi telah mengamankan pelaku dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan. Namun, fokus utama penyidik bukan hanya pada tindak pidana pembakaran, tetapi juga pada latar belakang psikologis dan kegagalan sistem pendidikan yang membiarkan penderitaan ini berlarut-larut.
“Kami tidak hanya akan memproses hukum. Kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan, ulama, dan psikolog untuk mengkaji ulang sistem pengawasan dan perlindungan mental santri di seluruh pesantren di Aceh,” tegas Kombes Joko.
Peran Ustadz, Orang Tua, dan Komunitas: Haruskah Menunggu Tragedi?
Kasus ini membangunkan kita semua. Ustadz yang mengajar kitab suci, tapi tidak mengajar empati. Orang tua yang mengirim anak ke pesantren demi “dibentuk”, tapi tidak pernah menanyakan “apakah kamu bahagia di sana?”. Teman-teman yang tertawa saat ada yang diejek, tanpa sadar mereka sedang menghancurkan jiwa seseorang.
Pondok Pesantren Babul Maghfirah, yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang taat dan disiplin, kini dihadapkan pada tantangan terbesarnya: bagaimana membangun kembali kepercayaan, bukan hanya fisik bangunannya, tapi juga kepercayaan santri terhadap lingkungan mereka sendiri.
Solusi yang Harus Segera Diterapkan
Sistem Pelaporan Rahasia: Setiap pesantren wajib menyediakan kotak saran dan saluran komunikasi anonim untuk laporan bullying, tanpa takut dihukum atau diejek.
Pelatihan Mental Health untuk Ustadz: Ustadz bukan hanya pengajar agama, tapi juga pendamping jiwa. Mereka perlu pelatihan dasar psikologi remaja dan deteksi dini trauma.
Konselor Santri: Setiap pesantren besar sebaiknya memiliki konselor atau pendamping kesehatan mental yang terlatih, dan bekerja secara independen dari struktur disiplin.
Kampanye Anti-Bullying Berbasis Nilai Islam: Ajarkan bahwa merendahkan orang lain adalah dosa, bukan “gurauan”. Ajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kelembutan, bukan kekerasan verbal.
Pesan Terakhir: Jangan Biarkan Diam Menjadi Ledakan
Kebakaran itu telah padam. Asrama mungkin bisa dibangun kembali. Tapi bagaimana dengan luka batin yang terus berdarah di hati santri-santri lain yang diam, takut, dan merasa tidak berharga?