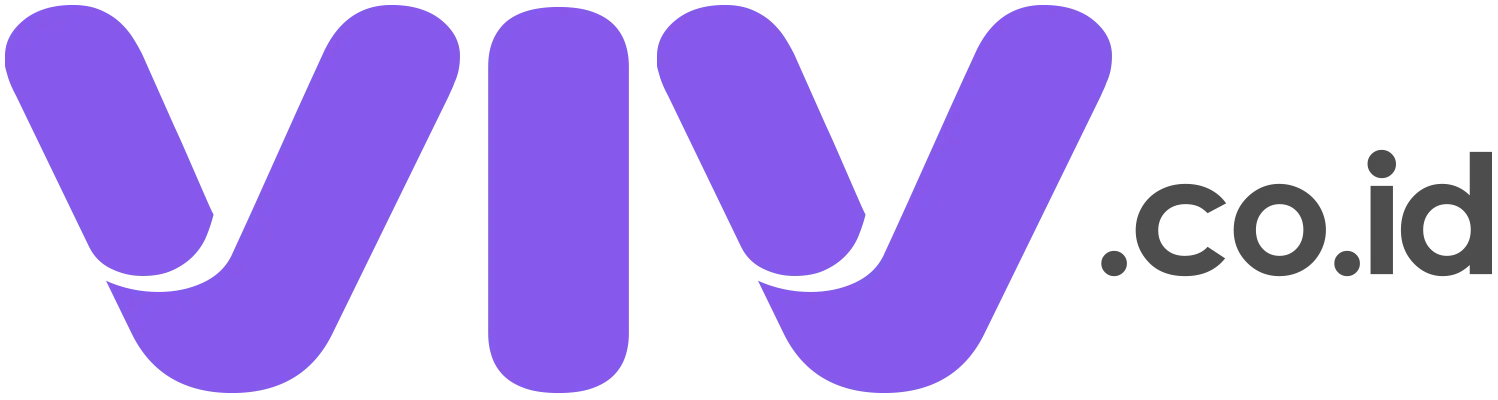Ulta Levenia Nababan Anaknya Siapa? Inilah Sosok Peneliti Konflik dan Terorisme Asal Bukittinggi yang Viral di Podcast Close The Door, Bukan Orang Sembarangan?

Ulta-Instagram-
Ulta Levenia Nababan Anaknya Siapa? Inilah Sosok Peneliti Konflik dan Terorisme Asal Bukittinggi yang Viral di Podcast Close The Door, Bukan Orang Sembarangan?
Analisis Cemerlang yang Bikin Netizen Terpana
Baru-baru ini, sebuah nama muncul sebagai bintang tak terduga di kanal podcast paling populer di Indonesia — Close The Door bersama Deddy Corbuzier. Bukan artis, bukan selebgram, bukan pula politisi. Tapi seorang perempuan berdarah Minang dari Bukittinggi, Sumatera Barat, yang ternyata memiliki kisah hidup luar biasa: Ulta Levenia Nababan, seorang peneliti konflik dan terorisme yang telah menyentuh wilayah paling rawan di dunia.
Dalam sesi wawancara yang berlangsung selama lebih dari dua jam, Ulta tidak hanya membahas teori-teori akademis tentang “Color Revolution” atau “relative deprivation”. Ia menggoyang pikiran jutaan pendengar dengan pengalaman lapangan yang nyaris tak percaya: bertemu Taliban di Afghanistan, masuk ke markas Abu Sayyaf di Filipina Selatan, bahkan diajak menikah oleh pemimpin kelompok bersenjata — semua dilakukan demi memahami akar radikalisme dari dalam.
Dan inilah kisah lengkapnya.
Siapa Sebenarnya Ulta Levenia Nababan?
Nama Ulta Levenia Nababan mungkin belum familiar di kalangan umum, tapi di lingkaran akademik keamanan nasional dan internasional, ia sudah dikenal sebagai salah satu ahli konflik bersenjata paling berani dan visioner di Indonesia. Perempuan kelahiran Bukittinggi, 1995, ini tumbuh di tengah budaya Minang yang kental akan nilai keilmuan dan keadilan sosial — sebuah latar belakang yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi misinya: memahami kekerasan agar bisa mencegahnya.
Ia bukan sekadar peneliti yang membaca laporan. Ia adalah pelaku sejarah yang hidup di dalamnya.
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI), Ulta memutuskan untuk melanjutkan studi magister di University of Leeds, Inggris, dengan spesialisasi Keamanan, Terorisme, dan Pemberontakan — salah satu program paling bergengsi di Eropa dalam bidang ini. Di sana, ia tidak hanya menulis tesis, tapi juga mulai merancang metodologi analisis yang menghubungkan faktor ekonomi, psikologis, dan geopolitik dalam munculnya gerakan radikal.
Namun, yang membuatnya benar-benar mencuri perhatian publik adalah bagaimana ia berhasil menggabungkan ilmu akademis dengan riset lapangan yang ekstrem — tanpa senjata, tanpa tim keamanan, tanpa protokol resmi. Hanya modal keberanian, empati, dan ketajaman analisis.
Pengalaman Lapangan yang Mengguncang Dunia: Dari Afghanistan hingga Filipina
Tidak seperti banyak peneliti yang hanya mengandalkan wawancara via Zoom atau data sekunder, Ulta melakukan pendekatan ground-level research. Ia masuk ke wilayah-wilayah yang dianggap “terlarang” oleh pemerintah maupun media mainstream.
1. Bertemu Taliban di Afghanistan
Di usia 24 tahun, Ulta pergi ke Afghanistan sendirian — tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia, tanpa dukungan lembaga internasional. Ia tinggal selama beberapa minggu di daerah pedesaan dekat Kandahar, berbaur dengan komunitas lokal, mendengarkan cerita para ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat serangan drone, dan berdiskusi panjang dengan tokoh-tokoh Taliban yang tidak ingin perang, tapi merasa tidak punya pilihan lain.
“Mereka bukan ‘monster’ seperti yang digambarkan media Barat,” ujarnya dalam podcast. “Mereka adalah manusia yang terjebak dalam sistem yang gagal. Ketika negara tidak hadir, kelompok bersenjata menjadi satu-satunya penyedia layanan, keadilan, bahkan rasa aman.”
2. Masuk Markas Abu Sayyaf — Dan Diajak Nikah
Di Filipina Selatan, tepatnya di pulau Mindanao, Ulta berhasil masuk ke salah satu basis kelompok Abu Sayyaf — organisasi bersenjata yang dikategorikan sebagai teroris oleh PBB dan ASEAN. Ia datang dengan membawa buku-buku tentang filsafat Islam dan perlawanan adil, serta membantu mengajar anak-anak di desa terpencil.
Selama seminggu, ia tinggal bersama keluarga pejuang. Suatu malam, pemimpin kelompok itu — seorang pria berusia 38 tahun yang kehilangan istri dan dua anaknya dalam operasi militer — secara tulus mengajaknya menikah.
“Dia bilang, ‘Kamu berbeda. Kamu tidak datang untuk menghakimi. Kamu datang untuk memahami.’ Saya menolak dengan sopan. Tapi saya tidak pernah lupa betapa tragisnya cinta yang lahir di tengah kehancuran.”
Pengalaman ini kemudian menjadi dasar penelitian terbarunya tentang “Emotional Radicalization” — bagaimana trauma, kesepian, dan rasa dicintai bisa menjadi pintu masuk paling efektif bagi rekrutmen teroris, lebih dari ideologi atau uang.
3. Menyaksikan Eksekusi Lapangan di Datu Saudi
Di wilayah Datu Saudi, Maguindanao, Ulta menjadi saksi mata atas eksekusi seorang warga sipil yang dituduh bekerja sama dengan tentara Filipina. Ia merekam suara tangisan ibu korban, catatan medis yang dibuat secara manual oleh relawan, dan dialog antara pemimpin lokal dengan anggota bersenjata yang tampak lelah — bukan marah.
“Ini bukan soal ‘baik vs jahat’. Ini soal sistem yang membiarkan orang-orang seperti ini merasa bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk didengar.”
Analisis Brilliance: Color Revolution dan Relative Deprivation di Indonesia
Ketika Deddy Corbuzier menanyakan tentang gejolak sosial di Indonesia tahun 2025 — mulai dari demo mahasiswa, isu harga bahan pokok, hingga viralnya narasi anti-pemerintah di media sosial — Ulta memberikan jawaban yang membuat ruangan hening.
Ia menjelaskan konsep Relative Deprivation — yaitu rasa ketidakadilan yang muncul ketika seseorang merasa dirinya layak mendapat lebih, tetapi tidak mendapatkannya, terutama saat melihat orang lain (sering kali di media) hidup mewah.
“Orang Indonesia tidak marah karena miskin. Mereka marah karena melihat seseorang yang sama latar belakangnya, bahkan kurang berprestasi, tiba-tiba punya mobil mewah, rumah di Bali, dan jalan-jalan ke Eropa — sementara mereka harus antri BBM dan gaji tidak cukup untuk beli telur.”
Lalu ia menyambung dengan analisis Color Revolution — gerakan protes yang diduga dimanfaatkan oleh aktor asing untuk menggulingkan pemerintahan sah melalui mobilisasi massa digital.
“Kita sedang mengalami ‘perang informasi’ yang sangat halus. Ada ribuan akun bot yang menyebarkan konten provokatif, ada dana asing yang mengalir ke LSM tertentu, dan ada influencer yang tanpa sadar menjadi alat propaganda. Semua ini dimainkan dengan sangat presisi — menggunakan emosi, bukan logika.”
Ia menekankan: Indonesia bukan target utama, tapi target ideal. Negara demokratis besar, populasi muda, tingkat literasi digital tinggi, tapi sistem keamanan nasional masih lemah dalam deteksi dini disinformasi.